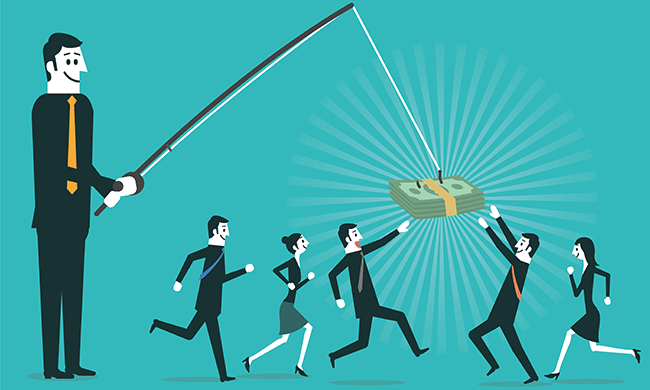Uang dan Kekuasaan
Jakarta, 2 November 2026 – Uang tak hanya alat tukar, tapi juga cermin jiwa manusia. Di balik lembaran dan angka digitalnya, uang menuntun perilaku, menakar ambisi, bahkan menentukan siapa yang punya suara dalam masyarakat. Artikel ini mengajak kita menelusuri sisi psikologis—simbol kekuasaan yang paling halus sekaligus paling kuat.
Uang bukan sekadar alat tukar. Ia adalah simbol kepercayaan, kekuasaan, dan—di era modern—identitas sosial. Dari koin logam di kerajaan Lydia 2.600 tahun lalu hingga mata uang digital hari ini, perjalanan uang selalu beriringan dengan perjalanan manusia memahami nilai, ambisi, dan rasa aman.
Sejarah menunjukkan, setiap kemajuan dalam sistem uang lahir dari krisis kepercayaan. Saat barter tak lagi efisien, muncul koin logam. Ketika koin terlalu berat, datang uang kertas. Lalu saat inflasi dan jarak membuat transaksi lamban, lahirlah sistem digital. Uang berubah bentuk, tapi fungsinya tetap: menciptakan kepercayaan di antara orang-orang yang tak saling kenal.
Uang Sebagai Alat Ukur Harga Diri
Dalam psikologi manusia, uang punya dimensi lebih dalam dari sekadar fungsi ekonomi sebagai alat tukar. Daniel Kahneman, peraih Nobel Ekonomi, menunjukkan bahwa uang memengaruhi persepsi kebahagiaan hanya sampai titik tertentu—sekitar US$75.000 per tahun dalam studi klasiknya. Di atas itu, uang lebih berperan sebagai simbol status dan rasa kontrol. Uang memberi ilusi kebebasan, bahkan sering kali menjadi sumber kecemasan baru.
Sebuah studi Harvard Business School (2021) menemukan, bahwa orang dengan orientasi finansial tinggi cenderung mengalami tingkat stres 13% lebih tinggi dibanding mereka yang menilai keberhasilan dari hubungan sosial. Artinya, kekuasaan uang bukan hanya ekonomi, tapi juga psikologis: ia mengatur cara kita merasa berharga.
Media sosial mempercepat efek ini. Nilai seseorang tak lagi diukur dari isi kepala, tapi dari harga barang yang bisa ia tampilkan. Dalam konteks ini, uang bukan lagi alat tukar, melainkan alat ukur harga diri. Dan ketika semua orang berlomba menunjukkan kemakmuran, perbedaan antara “aku memiliki” dan “aku adalah” menjadi kabur.
Mungkin di sinilah kita perlu kembali menafsirkan makna uang secara lebih reflektif. Bahwa uang memang memberi ruang pilihan, tapi tidak seharusnya menjadi dasar identitas. Dalam keseharian yang makin digital dan kompetitif, kekuatan sejati justru ada pada kemampuan menjaga jarak dengan uang—menggunakannya, bukan dikuasainya.
Karena pada akhirnya, kekuasaan uang hanya nyata sejauh kita mempercayainya. Dan kepercayaan, seperti halnya uang, selalu bisa dicetak ulang. Lalu, bagaimana menurut Anda jika ada yang mengatakan, “uang belum tentu membuat kita bahagia, tapi tanpa uang sudah pasti kita sulit untuk bahagia.” Anda setuju?